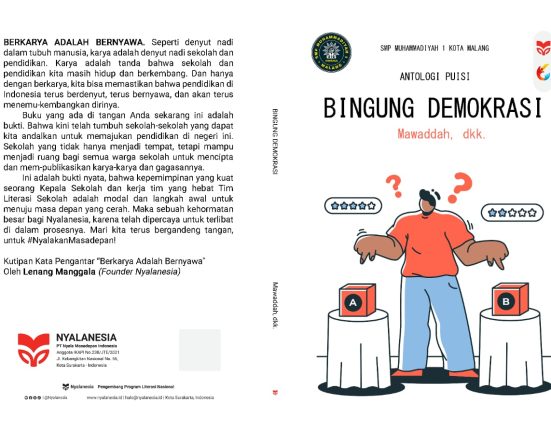Oleh: Adam Satria
Mahasiswa Prodi Studi Agama-Agama, Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Secara umum, institusionalisasi agama dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan legitimasi formal terhadap praktik agama tertentu melalui kebijakan atau peraturan negara. Dalam praktiknya, tujuan institusionalisasi ini adalah untuk melindungi nilai-nilai religius dan moral di masyarakat, sehingga negara dapat memastikan keberagamaan yang kondusif.
Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa institusionalisasi agama justru dapat berdampak negatif bagi masyarakat multikultural seperti Indonesia, terutama jika kebijakan tersebut mengarah pada bentuk “religious bias” atau keberpihakan negara terhadap agama-agama tertentu. Institusionalisasi ini kerap menghadirkan eksklusivitas, terutama dalam hal akses terhadap hak-hak kebebasan beragama (Hefni, 2020).
Penelitian menunjukkan bahwa ketika negara ikut campur terlalu jauh dalam mengatur agama, hal ini malah menciptakan ketegangan antara masyarakat yang mengidentifikasi dirinya dengan agama resmi versus agama non-resmi. Dalam konteks Indonesia, pengategorian agama menjadi resmi dan tidak resmi telah mengarah pada diskriminasi sosial bagi penganut agama-agama lokal atau kepercayaan yang tidak diakui negara (Hendardi, 2022).
Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, karena pada dasarnya keberagamaan bukan hanya tentang formalitas institusi, tetapi juga tentang kebebasan dan hak individu untuk memilih dan menjalankan keyakinannya.
Mengapa Ada Agama Resmi dan Tidak Resmi?
Pengategorian agama sebagai resmi atau tidak resmi sering kali didasarkan pada sejarah politik serta hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas dalam sebuah negara. Pada negara yang menerapkan agama resmi, agama tersebut biasanya mendapatkan lebih banyak dukungan dari pemerintah baik secara finansial, akses terhadap fasilitas publik, maupun pelindungan hukum.
Namun, studi dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa kebijakan ini sering kali mengarah pada marginalisasi agama-agama minoritas atau kepercayaan lokal yang dianggap tidak sesuai dengan standar “agama resmi” negara (Ramli, 2018). Kebijakan ini juga menjadi tantangan dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua warga.
Selain itu, dalam kajian teologis, keberadaan agama resmi dan tidak resmi dapat menciptakan kesenjangan akses terhadap fasilitas publik seperti pendidikan agama di sekolah atau akses layanan spiritual di lembaga pemerintah. Dalam pandangan akademisi, ketidaksetaraan ini berpotensi merusak integritas sosial dan menghancurkan kesatuan bangsa karena menciptakan diskriminasi dan eksklusivitas yang bertentangan dengan semangat Pancasila (Sutrisno, 2019).
Dampak Penginstitusian Agama terhadap Kebebasan Individu
Salah satu kritik terhadap institusionalisasi agama adalah bahwa kebijakan ini seringkali membatasi kebebasan individu dalam mengekspresikan keyakinan mereka. Dalam banyak kasus, kelompok agama minoritas sering menghadapi tantangan dalam memperoleh akses ke tempat ibadah atau dalam menjalankan ritual keagamaan mereka.
Sebagai contoh, penelitian di jurnal Kenosis menunjukkan bahwa dalam konteks digital pun, agama minoritas seringkali sulit mendapatkan pengakuan formal karena kebijakan pemerintah yang lebih mendukung agama mayoritas (Nalle, 2020). Tantangan ini semakin memperjelas bahwa institusionalisasi agama dapat mempersempit ruang bagi kebebasan beragama.
Di era digital ini, pembatasan semacam itu juga terlihat dari keterbatasan kelompok agama minoritas dalam mengekspresikan keyakinan mereka secara online tanpa takut diskriminasi atau sanksi sosial. Pengategorian agama resmi dan tidak resmi cenderung menciptakan eksklusivitas yang tidak mengakomodasi keragaman keagamaan yang ada.
Refleksi Surat Al-Kafirun Ayat 6
Dalam konteks institusionalisasi agama dan pembagian antara agama resmi dan tidak resmi, penting untuk merujuk pada ayat lakum dinukum waliyadin (QS Al-Kafirun: 6), yang menyatakan, “Untukmu agamamu, dan untukku, agamaku.”
Ayat ini diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam konteks dialog dengan kaum Quraisy, yang pada waktu itu menyembah berhala. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberagaman agama, termasuk praktik ibadah yang dilakukan oleh kaum Quraisy, yang meskipun berbeda dari ajaran Islam, tetap dianggap sebagai bentuk agama.
Refleksi dari ayat ini mengajak kita untuk memahami bahwa semua bentuk ibadah, termasuk menyembah berhala, merupakan bagian dari ekspresi spiritual manusia dan mencerminkan hak setiap individu untuk memeluk agama mereka.
Dalam konteks ini, institusionalisasi agama yang cenderung memberikan status resmi kepada satu agama dapat dianggap bertentangan dengan semangat toleransi yang terkandung dalam ayat tersebut. Hal ini sejalan dengan argumen bahwa keberagaman seharusnya diakui dan dihormati, bukan dipersempit atau didiskriminasi.
Oleh karena itu, dalam menanggapi dinamika sosial yang melibatkan agama, penting untuk mengingat bahwa institusionalisasi agama tidak hanya menciptakan batasan, tetapi juga dapat berkontribusi pada marginalisasi agama-agama yang tidak diakui secara resmi. Ayat ini mengingatkan kita bahwa pada hakikatnya, setiap orang memiliki hak untuk mengamalkan agamanya, dan dengan demikian, kebijakan pemerintah seharusnya mendukung keberagaman, bukan menghambatnya.
Penting juga untuk dicatat bahwa pemahaman terhadap ayat ini bukan hanya sekadar teologis, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang dalam. Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keragaman agama dan kepercayaan, kita perlu merangkul nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut untuk membangun masyarakat yang inklusif dan saling menghormati.
Dengan refleksi ini, diharapkan kita dapat lebih memahami tantangan yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan institusionalisasi agama dan mengingat pentingnya untuk selalu menghargai hak beragama setiap individu, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur’an.
Kesimpulan
Menginstitusionalisasi agama serta memberikan status resmi dan tidak resmi pada agama dapat menjadi ancaman bagi masyarakat yang menghargai pluralisme dan keadilan sosial. Kebijakan ini kerap kali tidak hanya mempersempit ruang bagi agama minoritas, tetapi juga menimbulkan masalah diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama.
Institusionalisasi agama dapat menghambat upaya inklusi sosial di Indonesia yang memiliki keanekaragaman agama yang tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, reformasi kebijakan yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman kepercayaan sangat diperlukan.
Dengan mempertimbangkan dinamika dan tantangan sosial yang muncul akibat institusionalisasi agama, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih terbuka dan fleksibel dalam mengelola keberagamaan di Indonesia. (*)