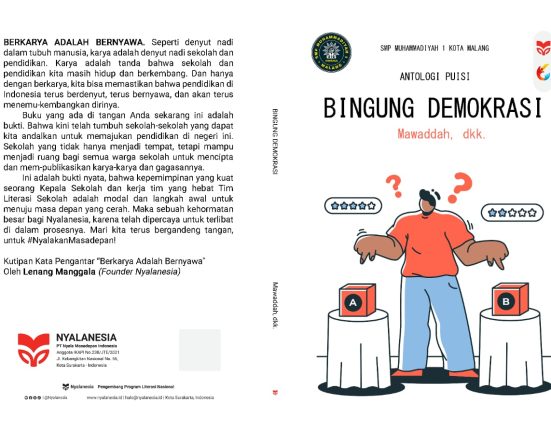Sumber: google.com
Sungguh haru, ketika melihat fenomena tentang membuminya gerakan gerakan hijrah yang di usung oleh pemuda pemudi di dunia maya maupun nyata sekitar dalam kurun waktu 2015-2017 lalu. Juga tidak terlepas dari peran akun-akun dakwah di instagram khususnya. Banyak dari para followersnya yang tadinya belum baik menjadi baik. Yang baik menjadi semakin baik. Bahkan yang belum tumbuh niat untuk menikah muda, dengan subur ia tumbuh menggebu didalam hati mereka untuk menyegerakannya. Dan masih banyak lagi. Kita patut mendoakan agar para pemegang saham instagram mendapatkan hidayah untuk bersyhadat. Agar peran sertanya dalam fenomena hijrah ini dapat menjadi amal shaleh di sisi Allah.
Tak perlu merekonstruksi makna hijrah itu sendiri. Tentunya kita semua mengerti bahwa arti hijrah secara umum adalah “perpindahan/berpindah”. Maka, kata kerja tersebut dapat kita gunakan untuk memahami isi tulisan ini lebih lanjut.
Hari ini kita sedang melalui gelombang masa fenomena (hijr)ah. Pun yang sebelumnya kita juga telah melewati gelombang masa fenomena hijrahnya ponsel kita yang dulu layar pixelnya masih ratusan, hijrah ke layar pixel yang jutaan. Bahkan lebih dari itu.
Pandangan mengenai fenomena (hijr)ah hari ini, secara umum lebih menitik beratkan kepada ukuran pakai peci atau tidak. Peci yaman atau peci lokal. Gamis atau sarung. Isbal atau tidak isbal. Berjenggot atau mulus. Kening hitam atau tidak. Bercadar atau tidak. Dan ukuran lahiriah lainnya yang dapat dijadikan parameter seseorang telah (hijr)ah (Tentunya kita juga berharap dan berusaha untuk hijrah dalam ukuran ruhaniah). Toh, muslim mana sih, yang tidak suka melihat saudara seimannya menjadi lebih baik?. Tapi apakah itu yang menjadi tolak ukur hijrah? Tentu saja tidak.
Memang, beberapa yang dalam konteks syariat, itu menjadi penting dan harus. Karena itu memasuki wilayah doktrinal dalam agama. Tetapi selebihnya, menjadi lebih penting karena itu adalah sumber gizi akal kita dalam konteks rasionalitas yang menjadi upaya untuk memahami agama secara utuh. Tidak secara parsial.
Pembaca budiman, hijrah memanglah penting. Tapi, memahami dan berupaya untuk hijrah dengan penuh kesadaran itu lebih penting.
Juga dalam rangka meneladani kisah-kisah hijrah para nabi dan rasul terdahulu (ittiba’). Salah satu kisah yang mungkin kita semua tahu, hijrahnya nabi Ibrahim dari Mesir, menuju kan’an bagian selatan palestina (bersama dengan istri keduanya (Hajar) dan anaknya Ismail), yaitu suatu lembah yang kering dan tandus sehingga tidak ada tumbuhan. Yang hari ini kita kenal dengan Makkah. (Waryono Abdul Ghafur, 2016) Dari kisah tersebut, tentu kita dituntut untuk dapat memahami pesan dan makna apa yang dapat kita teladani.
Berangkat dari kekhawatiran penulis, tentang ekspresi keberagamaan sebagian besar pemuda hari ini yang mempunyai potensi untuk berhenti pada aktifitas hijrah semata (terlepas dari tujuan untuk mendapatkan jodoh atau tidak). Berhenti pada aktifitas menghafal al-qur’an semata (meskipun jembatan untuk memahami dan mengamalkannya adalah dengan membaca dan menghafalkannya). Berhenti pada aktifitas ibadah syariat semata (sholat, puasa, zakat, & haji). Dan berhenti pada aktifitas dzikir serta doa semata.
Parameter penulis adalah karena sebagian besar dari kita hari ini, secara tidak sadar berhenti pada merekam dan menonton ceramah dalam bentuk visual oleh para ustad zaman now di youtube saja. Memilih memotret hasil presentasi ketimbang menulis dalam bentuk catatan di buku catatan kita. Alhasil, tumpukan buku dan jurnal yang sudah tersedia di perpustakaan jarang terjamah. Bersamaan dengan itu, sebagian besar dari kita yang terjebak dalam “zona nyaman” ketika para ustad tersebut memberikan suatu materi dalam metode ceramah dan tanya jawab yang hanya berkutat pada hitam putih dalam agama, tentang halal dan haram misalnya. Serta boleh begini atau tidak boleh begitu. Adapun yang menjelaskan lebih dari hukum, itu tidak banyak jumlahnya. Maka jangan heran, ketika terminologi dalam agama yang harusnya menjadi alat perekat, malah menjadi meresahkan didalam masyarakat. Seperti istilah “kafir”. Barangkali itu adalah dampak dari kurang luasnya ruang dialektis kita, yang ditandai dengan masih rancunya “frame” terminologi agama kita.
Memang, mencari ilmu agama harus dengan melalui perantara guru yang sanad keilmuannya sampai dan bersandar kepada Nabi saw. Tapi apakah proses pencarian kita secara naluriah itu tidak lebih penting? Bukankah seorang Ibrahim muda yang sebelum mendapatkan Wahyu dan menemukan Tuhannya, ia juga melalui proses pencarian yang luar biasa terlebih dahulu?
Terkadang kita terlena dengan indahnya retorika dan luasnya ilmu pengetahuan beliau-beliau sehingga menjadi menjadi sesuatu yang adiktif bagi kita. Penulis juga khawatir bahwa setelah kita puas mendengarkan dan terjawabnya pertanyaan-pertanyaan yang kita diajukan, itu menjadikan kita berhenti disitu. Dengan kata lain, kurangnya kesadaran dalam upaya proses pencarian kita.
Dengan begitu, ruang-ruang diskusi dan dialog interaktif pada majelis ilmu menjadi sempit. Maka, konsekuensinya adalah kita akan berhenti pada “menerima dan sebisa mungkin mengamalkan”. Terlebih “mandul” dalam membuahkan pemikiran-pemikiran segar dalam rangka merespon dan menafsir teks-teks suci Islam agar sesuai dengan kemajuan zaman.
Tidak sepenuhnya benar, juga tidak sepenuhnya salah.
Tapi jika memang begitu, kelak anak cucu kita malah hanya akan mendapatkan warisan romantisme hijrah dari para pendahulunya dulu (kita sekarang). Mereka malah justru “kurang kaya” dalam warisan karya intelektual yang harusnya kita hasilkan pada masa ini, apalagi karya monumental. Mereka tidak lagi menikmati tradisi keilmuan seperti para pemikir jauh sebelum masa kita, seperti perdebatan antara ibn rusyd dan socrates, imam ghazali dengan ibn rusyd, karl marx dengan paulo freire. Sampai dengan beberapa yang masih kita nikmati seperti Buya Syafii Maarif dan beberapa cendekiawan “muda” hari ini. Serta masih banyak yang lainnya.
Mereka (anak cucu kita) juga tidak lagi bisa menikmati bahkan menulis buku-buku literatur kontemporer pada masanya, kecuali sedikit dari mereka. Lebih dari itu, jika anak cucu kita nanti hanya mendapatkan warisan “karya-karya klasik” saja, maka besar kemungkinan mereka akan gagap dalam merespon fenomena keberagamaan yang terjadi pada zamannya. Salah satu penyebabnya adalah kita “terjebak” dalam romantisme hijrah pada masa ini.
Tapi mari kita lihat bagaimana model hijrah Muhammadiyah yang bisa kita baca melalui kerja-kerja pembaharuan Kiyai Dahlan dan murid-muridnya dulu. Muhammadiyah ormas yang berorientasi masa depan. Ia tidak hanya berdakwah pada mimbar-mimbar masjid saja. Tapi juga mengisi mimbar-mimbar sosial pada saat itu, hingga sekarang. Muhammadiyah yang senantiasa bergerak (baca; berhijrah) melalui gerak nyata dan pembaharuan pemikiran. Lebih daripada itu, pada awal berdirinya saja, ia sudah berpikir dan membangun ruang-ruang publik; sekolah, klinik kesehatan, panti asuhan yatim, yang sudah tidak lagi berorientasikan Islam saja, tapi juga kemanusiaan. Pun tidak perlu menghabiskan energi untuk menjelaskan bagaimana Islam rahmatan lil alamin. Apalagi dasar negara.
Model hijrah yang sudah lama digaungkan dan bernilai kebermanfaatan bagi orang banyak, sudah lebih dahulu dicontohkan oleh Muhammadiyah. Bahkan ia memaknai hijrah dengan sangat luas sekali. Tidak hanya hijrah yang hanya membawa perubahan yang berupa kebaikan pada diri sendiri (khoir). Tetapi juga membawa kebaikan-kebaikan bagi orang banyak (maruf).
Dengan demikian, sudah semestinya kita tidak boleh mempersempit arti hijrah itu sendiri. Yang mana, itu tercermin dari model gerakan dakwah yang kita lakukan. Sehingga kita tidak mengalami kebekuan dalam berpikir, yang pada ujungnya akan mengantar umat muslimin kejurang kemunduran dan tak dapat maju dan beradaptasi dengan peradaban.
Jika hari ini saja kita sudah mengalami krisis pemikir Islam yang menguasai kitab-kitab klasik dan mampu merespon ekspresi keberagamaan secara teks dan konteks kemajuan zaman (Ahmad Syafii Maarif, 2017), lantas bagaimana dengan anak cucu kita nanti?
Pembaca budiman, penulis hanya berharap adanya “balasan” tulisan tentang fenomena yang penulis bahas kali ini. Serta berharap adanya pembenaran-pembenaran pendapat didalamnya. Karena penulis merasa masih banyaknya celah kekurangan dalam tulisan ini.
Tentang memilih untuk sadar dalam fenomena, dan terjebak dalam fenomena, itu pilihan kita. Mari terus berhijrah dalam rangka mencari dan menemukan hakikat kebenaran. Wallahu a’lam.
*Penulis adalah Iman Permadi. Mahasiswa Studi Agama-agama di Universitas Muhammadiyah Surabaya.